Tulisan ini sama sekali bukan upaya untuk menjelaskan Buddhisme secara akademik. Ini cuma racauan yang (dibuat agak) tersruktur soal keinginan dan penderitaan setelah mencerna beberapa pemikiran Buddhisme. Jadi, pemikiran gua sama sekali tidak mewakili ajaran Buddha dan bisa saja melenceng jauh darinya.
Pergumulan dengan Buddhisme

Dalam seminggu terakhir, gua banyak membaca soal Buddhisme. Selama dua tahun ke belakang, sejak coba-coba belajar meditasi, pemikiran Buddha memang makin sering mampir ke dalam benak. Dan keinginan + penderitaan adalah dua konsep yang seringkali hadir ketika gua dihadapkan dengan Buddhisme. Jadi, “keinginan adalah sumber penderitaan” bukan sesuatu yang terdengar asing.
Di sisi lain, konsep keterjalinan keinginan dan penderitaan juga gua dapati dalam percakapan sehari-hari. Gua menyadari kalau, tanpa tendensi untuk menyadur Buddha, seseorang bisa meng-adopt pandangan hidup untuk meminimalisir keinginan. Bentuknya macam-macam: anti menabung (baca: nggak mau mengumpulkan kekayaan), menolak punya cita-cita, filosofi “ikut arus”, dan lainnya.
Kesadaran bahwa keinginan menempel erat dengan penderitaan juga tumbuh di agama lain. Lihat saja konsep syukur. Bukankah di dalamnya adalah pedoman untuk merasa cukup atas apa yang ada sekarang alih-alih mencari-cari (menginginkan) lebih?
Dalam Islam, gua pernah mendengar cerita dari Gus Baha tentang seorang santri dan kyai. Singkatnya, si kyai meminta santri untuk membelikan daging. Hanya saja, santri melapor kalau uangnya tidak cukup. Apa jawaban kyai? “Dibikin murah saja”. Si santri bingung, bertanya apa maksudnya. Jawaban si kyai: “ya jangan beli. Jadi, murah kan?” Kisah sederhana ini mencerminkan bagaimana menghilangkan keinginan justru bisa memudahkan hidup.
Akan tetapi, sejauh pemahaman gua, penderitaan dan keinginan memang menjadi begitu sentral dalam teks-teks Buddha. Ia tidak tersembunyi tetapi dijabarkan dengan eksplisit, jelas dan formal sebagai suatu sentral permasalahan. Hal inilah yang membuat ajaran Buddha jadi punya daya tarik yang kuat untuk gua. Ketika membaca teks atau mendengarkan lecture soal Buddha, gua tidak dihadapkan dengan pertanyaan soal Tuhan atau bahkan moralitas. Pertanyaan besar yang coba di-tackle justru adalah: “bagaimana cara menghilangkan penderitaan?”
Sebuah Paradoks
Jadi… apakah (dan jika iya, mengapa) keinginan adalah penderitaan?
Entahlah. Keinginan itu aneh. Gua pernah menulis soal menemukan keinginan yang otentik. Untuk menemukan keinginan yang benar-benar berasal dari diri. Tapi kalau pernyataan tersebut memang benar—bahwa keinginan akan membuat kita menderita, maka buat apa repot-repot punya keinginan? Hahaha.
Tapi, secara sekilas ketiadaan keinginan juga menghasilkan suatu kehidupan yang terasa suram. Kalau seseorang sudah tidak punya keinginan apapun, lantas selanjutnya apa yang tersisa? Maka buat apa ia hidup? Atau… justru jatuh ke dalam nihilisme? Nggak ada signifikansi. Nggak ada baik dan buruk. Semuanya dihalalkan. Maka, mengapa tidak membiarkan—atau membuat—dunia jadi kacau saja?
Eksplorasi singkat di atas membuat gua merasa penting untuk untuk berhati-hati dalam mencerna keinginan dan penderitaan. Toh, nyatanya Buddha—Siddharta Gautama—berkhotbah soal mencapai nirvana. Soal menghilangkan penderitaan. Ia punya titik tuju. Ajaran-ajarannya jadi pedoman supaya orang jadi selamat. In a way, Buddha ingin orang-orang selamat. Supaya tidak menderita. Kalau tidak, ngapain dia repot-repot ngajar dan menyebarkan ajarannya?
Tapi… bukannya keinginan adalah akar penderitaan? Malah jadi paradoks ya. Hahaha.
Arti dari Keinginan
Dalam konteks “keinginan adalah penderitaan”, gua mencerna keinginan yang dimaksud di dalam kalimat tersebut sebagai suatu act of clinging to something. Suatu keadaan terikat.
Keinginan adalah sesuatu yang kalau terjadi akan membuat lo merasakan kenikmatan (pleasure). Tapi kalau tidak terpenuhi akan membuat elo menderita. Jadi, kalau punya keinginan, elo akan clinging terhadap sesuatu yang elo inginkan untuk menjadi baik-baik saja. Elo jadi terikat.
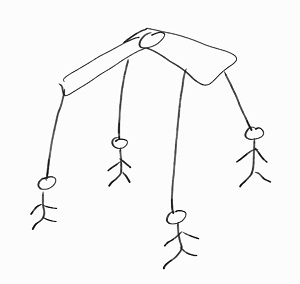
Pada dasarnya, klaim Buddha adalah kalau akar dari penderitaan adalah keinginan yang tidak terpenuhi ini. Itu saja. Penderitaan = keinginan yang tidak terpenuhi.
Jadi, gimana supaya tidak menderita? Jawabannya cuma dua: 1) menghilangkan keinginan; 2) mencapai semua keinginan tanpa terkecuali. Dan yang mungkin dilakukan cuma yang pertama.
Satu insight penting yang gua dapat dari cerita Buddha adalah bahwa semua orang pada akhirnya akan sakit, tua dan mati. Elo simply tidak bisa lari dari yang namanya kehilangan sesuatu. Keinginan paling primitif tentu adalah untuk terus hidup dan sehat. Tapi kita semua akan kehilangan keduanya. Tidak mungkin lari.
Itu baru satu keinginan mendasar. Tapi keinginan bisa mencapai bentuk yang tak terhingga. Wah, bisa banyak sekali. Dan lucu-lucu. Ingin lulus kuliah. Ingin makan nasi padang. Ingin bikin lagu yang bagus. Ingin minum kopi. Ingin minum kopi pakai pisang goreng. Man, kalau dipikir-pikir, ada banyak sekali hal sehari-hari yang kalau nggak terpenuhi bikin gua kesel. Hahaha.
Asal Muasal Keinginan
Lucunya… hal sehari-hari tadi kalau dipikir-pikir sebetulnya nggak perlu bikin kita menderita. Misalnya: minum kopi. Gua bisa kesel dan merasa “kurang” kalau tiba-tiba di rumah stok kopi sudah habis. Contoh lain: dapat komentar jelek pas presentasi. Gua bisa jadi bad mood.
Tapi: apakah harus seperti itu?
Buat gua, insights terbesar dari Buddhisme adalah untuk mempertanyakan keinginan-keinginan tadi. In a way, ajaran ini mengonstruksi ulang apa yang gua lihat sebagai masalah dalam hidup dengan cara yang sangat radikal. Apakah nggak bisa minum kopi adalah masalah? Apakah “dibantai” dosen adalah masalah? Hingga sampai pada hal-hal yang lebih mendasar… apakah merasa sedih adalah masalah? Apakah merasa kesal adalah masalah?
Mungkin… semua yang terjadi dengan diri gua—diomelin dosen, ditipu orang, diputusin pacar, ditimpa kesedihan, ditimpa kemarahan, dan seterusnya—bukanlah masalah. Mungkin, mereka baru jadi masalah ketika gua mempersepsikan mereka sebagai masalah. Mungkin, mereka baru jadi masalah ketika gua ingin mereka hilang. Mungkin, kalau gua melihat mereka sebagai sesuatu yang sudah seharusnya terjadi dan merasakannya dengan utuh tanpa upaya untuk mengubah apapun, mereka berhenti jadi masalah.
Mungkin… keterikatan yang lahir dari keinginan gua terhadap sesuatu hanyalah ilusi. Dan untuk melepaskan diri dari “rantai ilusi” tadi, gua cuma butuh merubah sudut pandang gua.
Pemahaman di atas jadi game changer. Ia sesuatu yang sangat praktikal, sesuatu yang bisa elo grasp lewat pengalaman sendiri. Caranya? Ya, sekali-kali kalau sedih, misalnya, jangan coba untuk menghilangkan kesedihan elo. Cukup dirasakan aja. Kalau kehabisan kopi, ya coba hidup semenit tanpa kopi. Rasakan. Pada level paling dasar, gua sadar kalau semuanya cuma aliran energi.
Tentu, kesadaran atau sudut pandang ini nggak setiap saat bisa dicapai. Butuh latihan. Dari 24 jam dalam sehari, paling gua cuma bisa mengalaminya secara pure selama semenit. Syukur-syukur 10 menit. Tapi gua tahu ia bisa dilatih. Ditingkatkan. Salah satunya, ya, lewat meditasi.
Konsep Diri
Ajaran Buddha kemudian mengajak gua untuk melacak keinginan dengan lebih jauh. Setelah menelusuri, ia mengantarkan gua pada konsep diri. Kenapa ada keinginan? Bagi Buddha (setidak-tidaknya sejauh yang gua pahami) sumbernya ada di dalam pemahaman mengenai diri. Ketika seseorang merasa memiliki diri yang harus dipuaskan, di situlah lahir keinginan.
Wah, di sini sudah mulai masuk ranah yang agak filosofis. Meskipun melihat Buddha sebagai suatu aliran filsafat sebenarnya bukan sesuatu yang tepat juga. Nanti kapan-kapan hal ini bakal gua bahas.
Bagi Buddha—atau setidaknya satu varian dari ajaran Buddha—diri dalam pengertian sehari-hari hanyalah ilusi. Misalnya, gua. Buat Buddha, keberadaan identitas bernama Hanif yang terus bertumbuh dan bertumbuh dari lahir sampai sekarang cuma ilusi. Hanif cuma ilusi. Terus hidup gua selama ini apa? Cuma kumpulan kesadaran yang saling menyusun satu sama lain. Nggak ada diri yang sejati. Nggak ada satu “inti” yang bisa nge-refer kepada entitas bernama Hanif. Nggak ada gua. Yang ada cuma kumpulan kesadaran yang saling terkait dan membentuk ilusi bahwa Hanif itu ada.
Fak. Ribet ya. Hahaha.
Apakah gua setuju dengan klaim ini? Entahlah. Masih mencerna. Buat gua, jawabannya tidak sesimpel: a) diri tidak ada; atau b) diri itu ada. Ditinjau dari satu sisi, diri itu ada. Ditinjau dari sisi lain, diri itu tidak ada. Ruwet. Ruwet.
Di sisi lain, gua percaya kalau elo bisa menghilangkan keterikatan (dan karenanya penderitaan)—setidaknya sampai tingkat tertentu— tanpa perlu kehilangan “diri”. Secara sederhana, caranya dengan belajar meditasi. Belajar untuk being presence. Lewat meditasi, gua belajar untuk “nrimo” dan “menari bersama apapun yang ada di dalam kesadaran”.
Dan, lucunya, konsep elo tentang “diri” memang jadi berubah setelah punya meditative experience. Kalau elo bener-bener mengikuti arus yang ada di present moment, “diri” nggak akan hilang dalam sekejap. Tapi, ia akan… terdifusi. “Diri” jadi lebih luas. Bergerak menjadi “latar” dalam kesadaran elo. Seperti satu titik tinta yang pelan-pelan menyebar jadi menyeluruh. Larut dengan air. Iya. “Diri” menjadi larut. Dan ketika larut, semua keterikatan jadi lepas dan yang ada cuma keadaan “baik-baik saja”.

Tanggung Jawab dan Hidup Melampaui Keinginan
Tapi, kesadaran bahwa keinginan adalah penderitaan nggak bisa menjawab pertanyaan sederhana soal makna: terus, buat apa hidup?
Apakah hidup cuma buat mengikis semua keinginan yang mungkin ada? Sampai akhirnya semua keinginan yang melekat hilang dan seseorang mencapai nirvana. Lepas dari lingkaran hidup-mati-kelahiran kembali.
Tapi… gua nggak begitu resonate dengan ide di atas. Intuisi gua mengatakan kalau ada sesuatu yang lebih dari sekadar mengikis keinginan.
Buat gua, hidup punya semacam Makna, Kebaikan, Dorongan, Tujuan—sesuatu semacam itu—yang membuatnya mesti dijalani. Gua merasa kalau hidup adalah ombak dan tugas gua cuma berselancar di atas ombak tersebut. Ibaratnya: tugas gua cuma menjadi gua yang seharusnya. Atau, mungkin lebih tepatnya, cuma hidup dengan seharusnya.
Dan untuk hidup dengan seharusnya, energinya lahir bukan dari mengikuti nafsu atau keinginan (dalam konteks keinginan yang clingy, yang membuat lo terikat), tetapi dari rasa tanggung jawab.
Rasa tanggung jawab yang lahir dari semacam intuisi mendasar terhadap apa yang baik dan yang buruk. Apa yang bermakna dan tidak bermakna. Nurani. Gua percaya ada sesuatu semacam itu. Jiwa. Nurani. Bisikan-bisikan yang sebetulnya selalu ada tapi seringkali tergencet oleh noise dari hidup elo yang terlalu kacau.
Rasa tanggung jawab yang lahir dari semacam intuisi kalau semuanya adalah pemberian. Semacam… gua diberikan tenaga, maka gua bekerja. Gua diberikan rasa, maka gua menikmati. Gua diberikan sense of good and evil, maka gua melakukan yang baik dan menjauhi yang buruk. Gua diberikan otak, maka gua berpikir. Sesuatu semacam itu.
Fak. Susah sekali mendeskripsikan hal ini dalam kata. Hahaha.
Tapi intinya gitu. Dan menurut gua tanggung jawab nggak perlu hadir dengan rasa terikat. Kalau elo berkeinginan atau terikat, tujuannya adalah sampai di tujuan. Sementara itu, tanggung jawab bukan soal sampai, tapi soal menuju. Tujuannya bukan mendapatkan, tetapi menjadi.
Gua rasa, keberadaan tanggung jawab ini jugalah yang menjadi energi bagi Buddha untuk menyebarkan ajarannya. Buddha tidak ingin orang-orang selamat, tetapi ia bertanggung jawab untuk membuat orang-orang selamat. Mungkin begitulah adanya.

Sedikit Penutup
Dalam sebuah buku tentang Buddhisme, gua menemukan ungkapan.
“Those who say do not know. Those who know do not say.”
Ungkapan ini seolah ingin bilang: “kalau elo ngomong, elo pasti salah”. Bahwa kebenaran tidak ada dalam kata-kata. Bahwa kebenaran hanya ada di dalam experience.
Yah, kata-kata gua mungkin tidak mengandung kebenaran barang setitik pun. Tapi gua berharap ia bisa jadi jembatan yang mengantarkan elo pada sebuah pengalaman yang didalamnya terdapat kebahagiaan, kebenaran dan rasa cukup yang penuh damai :)
Dah!